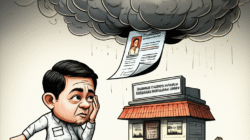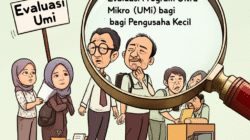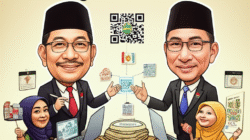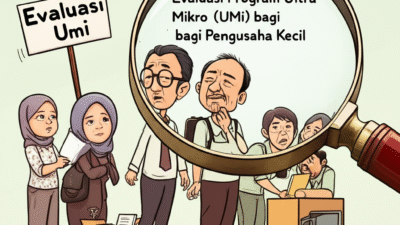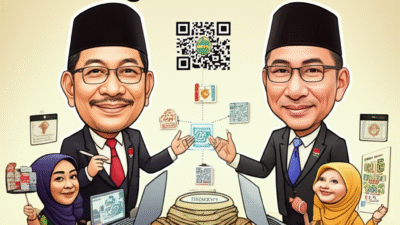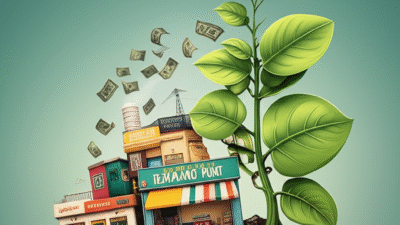Pedang Keadilan atau Pelanggaran Hak Asasi? Analisis Yuridis Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia
Pendahuluan: Dilema Abadi di Simpang Keadilan
Hukuman mati, atau pidana mati, adalah salah satu sanksi pidana tertua dalam sejarah peradaban manusia yang masih eksis hingga kini di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keberadaannya selalu menjadi episentrum perdebatan sengit, melibatkan spektrum argumen yang luas mulai dari aspek moral, etika, agama, sosiologi, hingga yang paling krusial, aspek hukum dan hak asasi manusia. Di satu sisi, ia dipandang sebagai manifestasi keadilan retributif yang setimpal bagi pelaku kejahatan luar biasa, serta instrumen ampuh untuk menciptakan efek jera dan melindungi masyarakat. Di sisi lain, ia dicap sebagai praktik yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, dan melanggar hak paling fundamental setiap individu: hak untuk hidup.
Di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait hukuman mati adalah cerminan dari tarik-menarik antara kedaulatan hukum nasional dalam memberantas kejahatan serius—khususnya narkotika dan terorisme—dengan desakan nilai-nilai hak asasi manusia universal dan tren global menuju abolisi. Artikel ini akan mengupas secara tuntas analisis yuridis terhadap kebijakan hukuman mati di Indonesia, menelaah landasan hukumnya, argumen pro dan kontra, implementasi di lapangan, serta dimensinya dalam konteks hukum internasional dan hak asasi manusia.
I. Landasan Yuridis Hukuman Mati di Indonesia: Pilar Konstitusi dan Undang-Undang
Keberadaan hukuman mati di Indonesia memiliki pijakan hukum yang kuat dan telah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Konstitusi (UUD 1945):
Pasal 28A UUD 1945 dengan tegas menyatakan, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Ayat ini seringkali menjadi landasan argumen bagi penentang hukuman mati. Namun, konstitusi juga menyediakan ruang bagi pembatasan hak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya (misalnya Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 dan No. 10/PUU-X/2012) menafsirkan bahwa hak untuk hidup bukanlah hak yang absolut dan dapat dibatasi demi kepentingan yang lebih besar, asalkan pembatasan tersebut diatur dalam undang-undang dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan. -
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
Pasal 10 KUHP secara eksplisit menyebutkan hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana pokok, di samping pidana penjara, kurungan, dan denda. Ini menunjukkan bahwa sejak era kolonial hingga kini, hukuman mati telah diakui sebagai sanksi legal. -
Undang-Undang Khusus:
Kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap luar biasa (extraordinary crimes) diancam dengan pidana mati dalam undang-undang khusus, antara lain:- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 111, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 123, 125, dan 127 mengatur pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dengan kategori tertentu, terutama pengedar dan bandar.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (jo. UU No. 5 Tahun 2018): Pasal 6, 7, 8, 9, 10, dan 15 mengancam pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme yang mengakibatkan kematian atau luka berat.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Pasal 7 mengatur tentang kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat diancam pidana mati.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan, Pasal 2 ayat (2) memungkinkan penerapan pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu, yaitu jika korupsi dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi dan moneter, atau pengulangan tindak pidana korupsi.
-
Putusan Mahkamah Konstitusi:
MK telah berulang kali menegaskan konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia, namun dengan beberapa syarat ketat. MK menekankan bahwa hukuman mati harus diterapkan secara selektif, sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), dan hanya untuk kejahatan yang sangat berat (most serious crimes). Selain itu, terdakwa harus diberikan seluruh haknya dalam proses hukum, termasuk hak banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), dan grasi.
II. Argumen Pro-Hukuman Mati: Perspektif Retributif dan Pragmatis
Pemerintah dan sebagian besar masyarakat yang mendukung hukuman mati mendasarkan argumennya pada beberapa pilar utama:
-
Efek Jera (Deterrence Effect):
Pendukung percaya bahwa ancaman kematian adalah disinsentif paling efektif yang dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Bagi mereka, hukuman mati bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengirimkan pesan kuat kepada calon pelaku kejahatan lain bahwa negara tidak akan menoleransi kejahatan serius. -
Keadilan Retributif (Retribution/Just Deserts):
Konsep "mata ganti mata" atau keadilan setimpal menjadi landasan kuat. Untuk kejahatan yang sangat keji seperti pembunuhan berencana massal atau peredaran narkoba yang merusak jutaan jiwa, hukuman mati dianggap sebagai balasan yang paling adil dan setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan. -
Perlindungan Masyarakat (Incapacitation):
Hukuman mati memastikan bahwa pelaku kejahatan yang sangat berbahaya tidak akan pernah lagi mengancam masyarakat. Meskipun pidana seumur hidup juga dapat mengisolasi pelaku, risiko pelarian atau pengulangan kejahatan (re-offending) di dalam penjara atau setelah bebas dianggap dapat dieliminasi sepenuhnya dengan eksekusi. -
Kedaulatan Hukum Nasional:
Bagi pendukung, penerapan hukuman mati adalah bagian dari kedaulatan negara dalam menentukan sistem hukumnya sendiri, tanpa intervensi dari negara atau organisasi internasional lain. Kebijakan ini dianggap sebagai cerminan kehendak rakyat yang ingin melihat kejahatan serius diberantas secara tegas. -
Pemberantasan Kejahatan Luar Biasa:
Terutama dalam konteks kejahatan narkotika dan terorisme, hukuman mati dipandang sebagai senjata pamungkas untuk memerangi sindikat kejahatan transnasional yang memiliki jaringan luas dan dampak destruktif masif.
III. Argumen Kontra-Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi dan Kemanusiaan
Kelompok anti-hukuman mati, yang terdiri dari aktivis HAM, organisasi sipil, dan sebagian akademisi hukum, mengajukan argumen yang tidak kalah kuat:
-
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Hak untuk Hidup):
Hak untuk hidup adalah hak fundamental yang tidak dapat dicabut (non-derogable right) dan melekat pada setiap individu sejak lahir. Eksekusi mati dipandang sebagai pelanggaran langsung terhadap hak ini dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. -
Risiko Kesalahan Peradilan (Irreversible Error):
Sistem peradilan manusia tidak sempurna. Ada kemungkinan, sekecil apa pun, bahwa individu yang tidak bersalah dihukum mati. Kesalahan semacam ini, jika terjadi, tidak dapat diperbaiki. Ini adalah argumen yang sangat kuat dan sering menjadi titik balik bagi banyak negara untuk menghapus hukuman mati. -
Tidak Efektif sebagai Efek Jera:
Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa tidak ada bukti konklusif yang membuktikan bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan pidana penjara seumur hidup. Kejahatan seringkali dilakukan secara impulsif atau di bawah pengaruh zat, di mana ancaman hukuman tidak menjadi pertimbangan utama. -
Diskriminasi dalam Penerapan:
Terdapat kekhawatiran serius tentang potensi diskriminasi dalam penerapan hukuman mati, baik berdasarkan status sosial-ekonomi, ras, etnis, maupun kemampuan akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Mereka yang miskin dan tidak mampu menyewa pengacara berkualitas seringkali lebih rentan dijatuhi hukuman mati. -
Kekejaman dan Tidak Manusiawi:
Apapun metode eksekusinya, hukuman mati dianggap sebagai bentuk penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, bertentangan dengan nilai-nilai peradaban modern. -
Tren Global Menuju Abolisi:
Sebagian besar negara di dunia telah menghapus hukuman mati, baik secara hukum maupun dalam praktik. Indonesia dianggap tertinggal dari tren global ini dan menghadapi tekanan internasional untuk menghapusnya atau setidaknya menerapkan moratorium.
IV. Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya: Antara Ketegasan dan Pertimbangan
Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap hukuman mati menunjukkan karakteristik yang unik, menggabungkan ketegasan dalam penegakan hukum dengan proses hukum yang berlapis dan ruang bagi pertimbangan kemanusiaan.
-
Fokus pada Kejahatan Narkotika:
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan eksekusi mati di Indonesia sangat fokus pada kasus narkotika. Pemerintah berargumen bahwa Indonesia berada dalam "darurat narkoba" yang mengancam generasi muda, sehingga penegakan pidana mati dianggap sebagai langkah ekstrem namun perlu untuk menyelamatkan bangsa. -
Proses Hukum Berlapis:
Terdakwa yang diancam pidana mati memiliki hak untuk menempuh berbagai upaya hukum:- Banding: ke Pengadilan Tinggi.
- Kasasi: ke Mahkamah Agung.
- Peninjauan Kembali (PK): dua kali (sebelum Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013) kini dibatasi satu kali, meskipun dalam praktiknya masih ada celah untuk lebih dari satu kali jika ditemukan novum yang substansial.
- Grasi: Permohonan pengampunan kepada Presiden Republik Indonesia. Grasi adalah hak prerogatif Presiden dan merupakan upaya hukum terakhir yang dapat menyelamatkan terpidana mati dari eksekusi. Proses grasi seringkali menjadi sorotan karena menjadi titik penentu akhir nasib terpidana.
-
Diskresi Eksekutif:
Jaksa Agung sebagai pemegang kendali eksekusi memiliki diskresi dalam menentukan waktu dan urutan eksekusi, meskipun ia terikat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan penolakan grasi oleh Presiden. -
Dilema Internasional:
Pemerintah Indonesia secara konsisten mempertahankan haknya untuk menerapkan hukuman mati sebagai bagian dari kedaulatan hukumnya, meskipun menghadapi kecaman dan tekanan diplomatik dari negara-negara yang warganya dieksekusi atau dari organisasi HAM internasional.
V. Dimensi Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia: Norma Global dan Tantangan Lokal
Hukum internasional, khususnya instrumen hak asasi manusia, memainkan peran signifikan dalam perdebatan tentang hukuman mati.
-
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR):
Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pasal 6 ICCPR mengakui hak untuk hidup, namun juga menyatakan bahwa dalam negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman mati hanya boleh dijatuhkan untuk "kejahatan yang paling serius" (most serious crimes) sesuai dengan hukum yang berlaku saat tindak pidana dilakukan, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Kovenan. Lebih lanjut, disebutkan bahwa setiap orang yang dijatuhi hukuman mati berhak mengajukan permohonan pengampunan atau peringanan hukuman. -
Protokol Opsional Kedua ICCPR:
Protokol Opsional Kedua ICCPR, yang bertujuan untuk penghapusan hukuman mati, belum diratifikasi oleh Indonesia. Ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk tidak terikat secara hukum internasional untuk menghapuskan hukuman mati. -
Hukum Kebiasaan Internasional dan Tren Abolisi:
Meskipun bukan norma hukum wajib, tren global menuju abolisi hukuman mati semakin kuat. Banyak negara menganggap penghapusan hukuman mati sebagai bagian dari evolusi norma hak asasi manusia universal. Komite Hak Asasi Manusia PBB (badan pengawas ICCPR) secara konsisten menginterpretasikan Pasal 6 ICCPR sebagai langkah menuju penghapusan hukuman mati. -
Implikasi Bagi Indonesia:
Posisi Indonesia sebagai negara yang masih mempertahankan hukuman mati menempatkannya dalam posisi yang unik di kancah internasional. Meskipun secara yuridis tidak melanggar kewajiban ICCPR (karena Pasal 6 masih memperbolehkan hukuman mati untuk kejahatan paling serius), tekanan diplomatik dan moral tetap menjadi tantangan, terutama dari negara-negara yang menganut abolisionisme.
VI. Prospek Masa Depan dan Rekomendasi Yuridis
Melihat kompleksitas dan dinamika perdebatan hukuman mati, beberapa rekomendasi yuridis dapat diajukan untuk kebijakan pemerintah Indonesia ke depan:
-
Evaluasi Komprehensif:
Melakukan evaluasi mendalam dan transparan terhadap efektivitas hukuman mati dalam menekan angka kejahatan, terutama narkotika. Data empiris yang kuat diperlukan untuk mendukung atau menyanggah klaim efek jera. -
Pembaharuan KUHP:
Dalam proses reformasi KUHP yang sedang berlangsung, penting untuk mempertimbangkan kembali relevansi hukuman mati dan potensi alternatif yang lebih manusiawi, seperti pidana penjara seumur hidup tanpa remisi atau pembebasan bersyarat. KUHP baru yang telah disahkan memang memperkenalkan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati, memberikan kesempatan bagi perubahan perilaku, yang bisa menjadi langkah awal menuju abolisi de facto. -
Perlindungan Hak Tersangka/Terpidana Mati:
Memastikan bahwa seluruh hak-hak hukum terpidana mati, termasuk hak atas bantuan hukum yang berkualitas sejak awal proses, hak untuk banding, kasasi, PK, dan grasi, terpenuhi secara mutlak dan transparan. Penting untuk meminimalisir risiko kesalahan peradilan. -
Pertimbangan Moratorium atau Abolisi Bertahap:
Meskipun abolisi total mungkin belum realistis dalam waktu dekat, pemerintah dapat mempertimbangkan moratorium eksekusi sebagai langkah awal, memberikan ruang untuk dialog publik yang lebih luas dan kajian mendalam. Ini akan sejalan dengan tren global dan mengurangi tekanan internasional. -
Fokus pada Pencegahan dan Rehabilitasi:
Menggeser fokus dari retribusi ekstrem ke pencegahan kejahatan yang lebih efektif, pemberantasan akar masalah kejahatan, serta program rehabilitasi yang komprehensif bagi pelaku dan korban.
Kesimpulan: Mencari Titik Keseimbangan
Analisis yuridis terhadap kebijakan hukuman mati di Indonesia mengungkapkan sebuah lanskap hukum yang kompleks, di mana prinsip kedaulatan negara dan kebutuhan memberantas kejahatan serius berhadapan langsung dengan nilai-nilai hak asasi manusia universal. Meskipun konstitusi dan undang-undang di Indonesia secara eksplisit memungkinkan penerapan hukuman mati, perdebatan moral, etika, dan kemanusiaan akan terus membayangi.
Kebijakan pemerintah Indonesia menunjukkan ketegasan dalam menghadapi kejahatan luar biasa, namun juga menyediakan mekanisme hukum berlapis untuk memastikan keadilan. Tantangan ke depan adalah bagaimana Indonesia dapat menyeimbangkan antara kebutuhan penegakan hukum yang tegas dengan penghormatan maksimal terhadap hak asasi manusia, serta bagaimana merespons tren global menuju penghapusan hukuman mati tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada akhirnya, keputusan tentang "pedang keadilan" ini akan terus menjadi ujian bagi komitmen Indonesia terhadap keadilan substantif dan peradaban yang berlandaskan kemanusiaan.